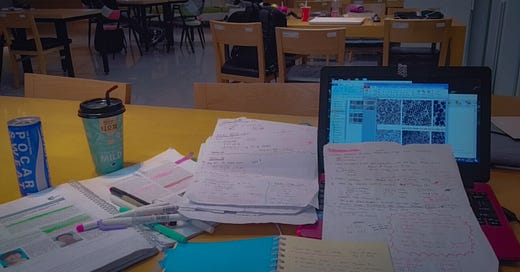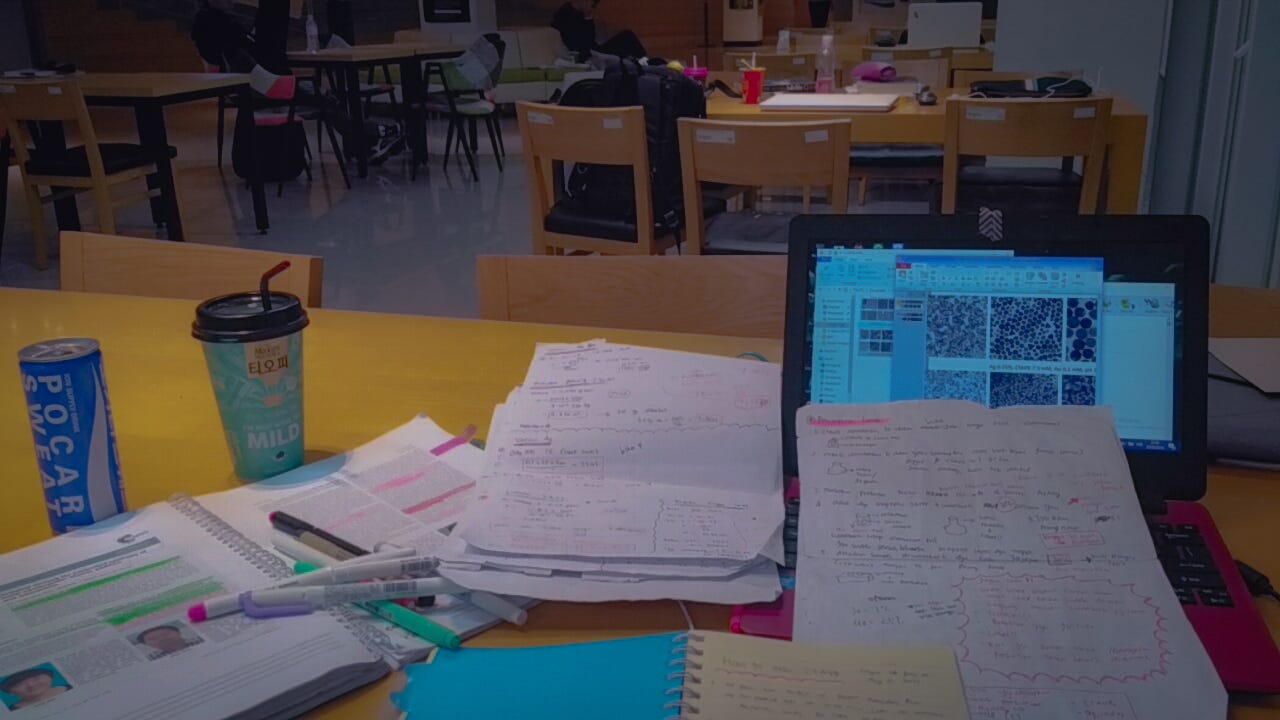Nostalgia Skripsi: Dari Depok ke Daejeon
Berbagi kisah bagaimana laboratorium dan ruang riset membuat saya tak hanya belajar sains—tapi juga belajar gagal, berpikir, dan menjadi manusia. Sebuah nostalgia cerita lama, tapi selalu terkenang.
⚠️ Catatan: Tulisan ini cukup panjang. Kalau kamu sedang membaca sambil menunggu kopi diseduh atau sekadar iseng di sela-sela jam makan siang, mungkin ini bukan saat yang tepat. Tapi kalau kamu sedang ingin menyelami kembali kenangan, merenungi pilihan-pilihan akademik, atau sedang berpikir untuk menempuh riset di luar negeri, tulisan ini bisa jadi teman yang pas.
Dari Universitas Indonesia ke KAIST
Perjalanan Skripsi yang Tak Terlupakan
Beberapa tahun lalu, saya mendapatkan kesempatan langka yang hingga kini tetap saya anggap sebagai titik balik penting dalam hidup: menyelesaikan skripsi di luar negeri, di kota Daejeon, Korea Selatan. Musim dingin menyambut saya saat itu—dingin yang nyata, menusuk hingga tulang, bukan sekadar metafora. Ini adalah kali pertama saya merasakan suhu minus dua puluh derajat Celsius, dan saya jelas tidak siap. Jaket saya terlalu tipis, kulit saya mengelupas, dan setiap hembusan angin terasa seperti hukuman dari dewa musim.

Saya datang sebagai mahasiswa S1 Kimia dari Universitas Indonesia, ditempatkan di Nano Scattering and Nanoscale Material Lab di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology). KAIST bukan tempat main-main. Laboratoriumnya padat teknologi, ekspektasinya tinggi, dan budaya kerjanya tak kenal kompromi. Saya dibimbing langsung oleh Prof. Sung-Min Choi, profesor teknik nuklir yang spesialisasinya nanoscale materials dan teknik scattering. Tipikal pembimbing yang tidak mengenal kata "suruh" tanpa contoh, dan tidak pernah menjelaskan sesuatu secara setengah-setengah. Ia memberikan pertanyaan-pertanyaan tajam, tanggapan langsung terhadap data, dan selalu menantang saya untuk tidak hanya mencari hasil, tapi mengerti konteksnya. Keras, tapi logis. Di bawah bimbingan beliau, saya bukan sekadar mahasiswa, tapi mitra intelektual yang diajak berpikir serius.
Kehidupan saya di Daejeon terasa seperti montase film indie: pertama kali naik pesawat, pertama kali hidup tanpa orang tua, pertama kali berhadapan dengan salju, dan pertama kali sadar bahwa salju ternyata tidak selalu putih dan romantis seperti di drama Korea. Saya di sana hanya beberapa bulan, tidak lama, tapi di saat yang sama pula saya merasakan pertama kali indahnya sakura mekar di musim semi serta betapa sepinya musim dingin.
Hidup sendirian di kota asing, dengan bahasa yang tidak saya kuasai, membuat saya harus belajar hal-hal yang sebelumnya tak pernah saya pikirkan. Saya belajar cara mencuci baju di mesin cuci yang semua tulisannya dalam Hangul. Dan saya belajar bahwa satu-satunya cara bertahan adalah dengan memelihara rasa ingin tahu yang lebih besar dari rasa takut.
Kenapa Nanopartikel? Kenapa Emas? Kenapa Oktahedron?
Saya bukan ahli matematika. Persamaan diferensial pernah membuat saya ingin menyerah. Tapi saya selalu punya ketertarikan pada struktur—pada tatanan terkecil dari dunia materi. Kimia anorganik dan fisik membuka dimensi visual yang bagi saya nyaris puitik. Di sinilah nanopartikel emas (AuNP) masuk.
Uniknya, emas yang kita kenal sebagai logam kuning bisa berubah menjadi merah, ungu, bahkan biru kehitaman, hanya karena ukurannya menyusut ke skala nanometer. Ini bukan sihir—ini resonansi plasmon permukaan lokal. Fenomena kuantum yang menyamar sebagai keajaiban optik. Dalam ukuran di bawah 100 nanometer, interaksi cahaya dan elektron berubah total. Emas bukan lagi emas yang kamu kenal.
Bentuk oktahedron memiliki faset {111} yang memberikan kestabilan dan keunikan reaktivitas kimia. Dalam ranah seperti katalisis atau surface-enhanced Raman scattering (SERS), bentuk ini bukan sekadar pilihan estetika, tapi juga teknis. Ini seperti memilih bentuk sayap yang paling aerodinamis untuk pesawat.
Tapi membentuk nanopartikel emas berbentuk oktahedron secara seedless—tanpa partikel bibit awal—adalah tantangan tersendiri. Metode seeded-growth memberi kontrol arah pertumbuhan kristal, tapi metode seedless menuntut sistem reaksi yang sangat presisi: suhu, pH, jenis surfaktan, hingga waktu reaksi harus disetel nyaris sempurna. Ini adalah eksperimen yang berjalan di ujung presisi dan intuisi tanpa toleransi terhadap kegagalan.
Eksperimen, Kegagalan, dan Kemenangan Kecil
Judul skripsi saya:
Seedless synthesis of octahedral gold nanoparticles with tunable sizes.
Saya menggunakan surfaktan CTAVB (cetyltrimethylammonium vinyl benzoate), dengan kombinasi HCl dan AgNO₃ sebagai penstabil dan agen pengarah kristal. Hasil terbaik? AgNO₃ 0.75%, suhu 30 ºC, waktu reaksi enam hari. Lama? Ya. Tapi dalam dunia kristalisasi seedless, itu kompromi yang perlu.
Menunggu enam hari hanya untuk menemukan bahwa bentuknya tidak sesuai harapan adalah pengalaman yang menampar ego. Tapi ketika akhirnya citra TEM menampilkan partikel-partikel solid, simetris, dan cantik dalam dalam bentuk oktahedron, rasanya seperti memenangkan pertempuran kecil yang hanya saya dan lab yang tahu betapa sulitnya. Disini saya belajar, dalam eksperimen: terkadang hasil dipengaruhi hal-hal yang tampaknya sepele.
Budaya Riset Korea dan Filosofi Ppali-Ppali
Korea Selatan bukan hanya negara teknologi, tapi juga negara kecepatan. Budaya kerja mereka dikenal dengan istilah ppali-ppali (빨리 빨리)—"cepat-cepat". Tidak hanya dalam layanan publik atau transportasi, tapi juga dalam budaya akademik. Saya sering bekerja hingga jam 2 pagi, balik ke asrama, tidur sebentar. Kembali lagi ke laboratorium jam 8 atau bahkan jam 7 pagi. Bukan karena dipaksa, tapi karena ritme kerja di sana memang seperti itu: efisien, intens, dan tak kenal ampun. Seolah waktu adalah satuan moral. Waktu saya di sana terbatas dan semua data harus segera selesai sebelum saya kembali ke Indonesia. Ritme penelitian dan urgensi waktu mengejar saya.
Budaya riset di KAIST berbeda jauh dari apa yang saya alami di Indonesia. Di sana, laboratorium berjalan hampir seperti perusahaan rintisan—setiap orang punya peran, target, dan tenggat. Tidak ada tempat untuk “nanti saja”, apalagi untuk sekedar ikut-ikutan.
Tapi bukan berarti suasananya kaku. Justru karena semua orang sibuk, setiap percakapan jadi berarti. Ketika saya ditanya oleh senior postdoc soal kenapa saya memilih oktahedron, saya tahu pertanyaan itu bukan basa-basi. Mereka mengharapkan jawaban yang konseptual, bukan sekadar prosedural. Saya belajar membaca citra TEM sendiri, mendiskusikan hasil SEM seperti mahasiswa pascasarjana, dan diajak berdiskusi langsung oleh peneliti postdoc. Semua ini membuat saya tumbuh cepat—dengan tekanan yang tinggi, ya, tapi juga dengan rasa tanggung jawab yang tidak bisa dibeli dengan teori.
Daejeon: Kota yang Tidak Glamor Tapi Jujur
Banyak orang membayangkan Korea Selatan lewat lensa Seoul: Gangnam, Myeongdong, atau drama Korea. Tapi Daejeon? Kota yang lebih sunyi. Bahkan musim dinginnya lebih dingin daripada Seoul—walau tentu tidak sedingin Pyeongchang. Tidak banyak atraksi turis. Tidak ada gedung gemerlap. Tapi Daejeon mengajarkan saya tentang kesunyian yang produktif. Di sinilah saya berkenalan dengan keseharian yang disusun oleh eksperimen, diskusi lab, dan perjalanan kaki melintasi sungai yang membeku.
Musim dingin kala itu menggigit lebih dalam dari yang saya perkirakan, dan bahkan sekadar berbelanja bahan makanan pun menjadi tantangan: saya harus menyeberangi sungai kecil melalui pijakan-pijakan batu yang licin karena es. Saya yang lahir dan besar di iklim tropis, belum pernah membayangkan akan bergulat dengan batu-batu beku demi nasi instan dan ramyun. Jujur, saya kaget saat pertama kali tahu bahwa melompati pijakan bebatuan untuk menyebrangi sungai kecil adalah hal biasa. Hal baru untuk saya yang besar di Jakarta.


Sehabis dinginnya salju, musim semi pun menyapa. Pengalaman pertama melihat sakura bermekaran, indah sekali.
Dan justru di kota inilah, saya mengenal sisi lain dari hidup. Sisi yang lebih dalam, lebih tenang, dan kadang lebih menyentuh. Saya tidak akan melupakan hari-hari ketika satu-satunya penghibur saya adalah ramen, makan es krim di tengah dinginnya malam musim dingin, dan ucapan teman saya, Siti Annissa, yang juga sedang meneliti sambil menyusun skripsinya sendiri. Kami berbagi cerita, kelelahan, bahkan tawa pahit ketika eksperimen gagal dan hari sudah lewat tengah malam. Ia adalah partner lab yang punya etos kerja tinggi, dan juga ulet. Dalam obrolan simpel itu, kami menyadari jenis ketangguhan yang tak bisa dibentuk di kelas—hanya bisa ditempa di lapangan.
Bimbingan, Pertanyaan, dan Refleksi
Saya juga dibimbing oleh dua dosen dari Kimia UI—Bu Aminah dan Bu Yuni—yang tidak hanya membimbing isi skripsi saya, tapi juga cara berpikir saya. Mereka tidak pernah memberi jawaban langsung, tapi selalu mengembalikan pertanyaan: Apa yang kamu cari dari riset ini? Kenapa kamu melakukan hal ini itu? atau Kalau kamu gagal, apa yang bisa kamu pelajari dari kegagalan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu rasa nyaman dan ketenangan, tapi justru itulah yang membentuk struktur berpikir saya hari ini.
Mereka adalah tipe dosen yang tidak banyak bicara, tapi tajam dalam mengarahkan. Sekali beliau bicara, saya langsung tahu saya harus mengganti pendekatan. Saya bersyukur dibimbing oleh mereka berdua—tidak hanya karena ilmu, tapi karena integritas mereka sebagai pendidik.
Dan tentu saja, saya tidak bisa menulis refleksi ini tanpa menyebut Prof. Sung-Min Choi. Beliau bukan hanya memberi saya tempat di lab, tapi memperlakukan saya dengan sangat baik. Beliau mengingat nama saya—saat itu, memberi saya ruang untuk menjelaskan temuan saya serta kendala penelitian saya di lab, dan sesekali bertanya balik kepada saya. Dalam dunia akademik yang hirarkis, sikap ini langka. Dan saya akan selalu mengingatnya.
Penutup: Dari Dingin Daejeon Menuju Panasnya Proses Menjadi Manusia Berpikir
Kini, saat saya menengok kembali pengalaman itu, rasanya seperti membuka catatan kaki dalam hidup saya yang paling berharga. Skripsi bukan sekadar tiket kelulusan. Ia adalah latihan berpikir. Latihan gagal. Latihan memahami diri sendiri. Ia adalah ruang untuk mencoba menjadi ilmuwan sebelum kita benar-benar jadi satu.
Saya belajar bahwa menjadi intelektual bukan hanya soal cerdas atau punya IPK tinggi. Tapi soal kesabaran. Soal berani mengakui kesalahan. Soal duduk lama di depan citra TEM dan bertanya: Kenapa bentuknya begini? Apa yang salah?
Saya belajar bahwa bekerja keras bukan berarti mengorbankan diri, tapi menyusun ulang prioritas. Dan bahwa keberanian bukan hanya soal pergi ke negeri asing, tapi juga soal mengakui bahwa kita tidak tahu, dan bahwa kita mau belajar.
Kalau kamu sedang menulis skripsi, sedang patah arang di tengah eksperimen, atau merasa risetmu tidak berarti—ingatlah: bahkan bentuk partikel sekecil nanometer pun butuh waktu enam hari untuk tumbuh sempurna. Dan kamu juga, mungkin sedang dalam proses itu.
Kita semua sedang menulis skripsi kita masing-masing, dalam bentuk yang berbeda-beda.
Dan mungkin, justru di situlah kita sedang belajar menjadi manusia.
Dari Runnilune, yang masih terus belajar.
Ditulis oleh Raihan Khairunnisa.
tags: bahasa indonesia, experience, photo(s)
If this piece resonates with you, feel free to share your own story—maybe a memory from the lab, a half-written thesis, or simply how research (or writing) has changed the way you think. I’m always curious about the inner processes behind other people’s work. :)
Thank you for reading.
If this sparked any useful overthinking, quiet epiphanies, or narrative spirals you didn’t ask for, feel free to fuel the next one with a cup of caffeine. Preferably overpriced. At a café where I pretend to write but mostly observe human absurdity.
No pressure. Just deeply caffeinated gratitude. :D